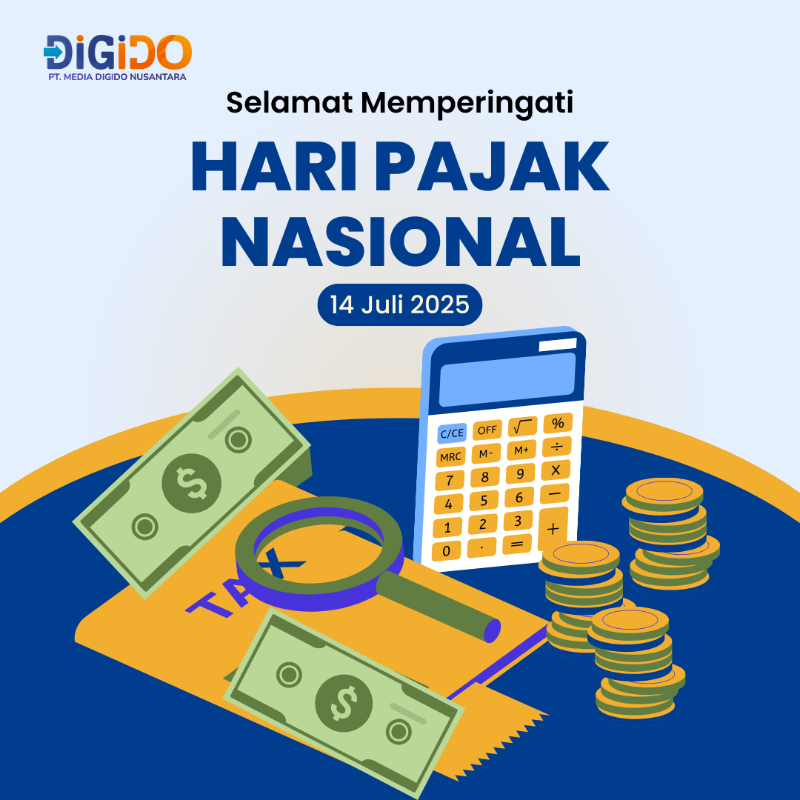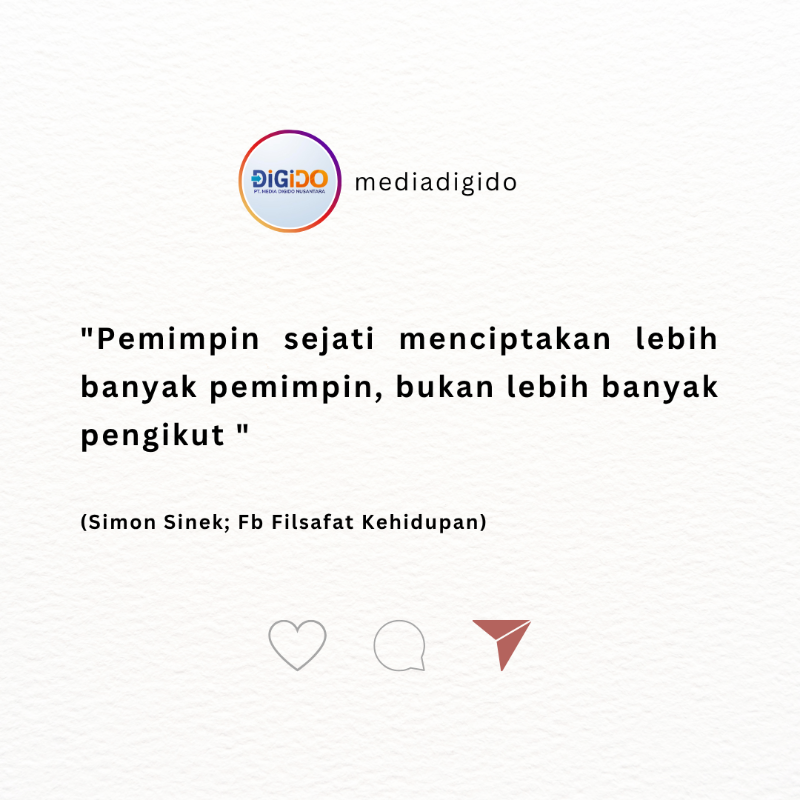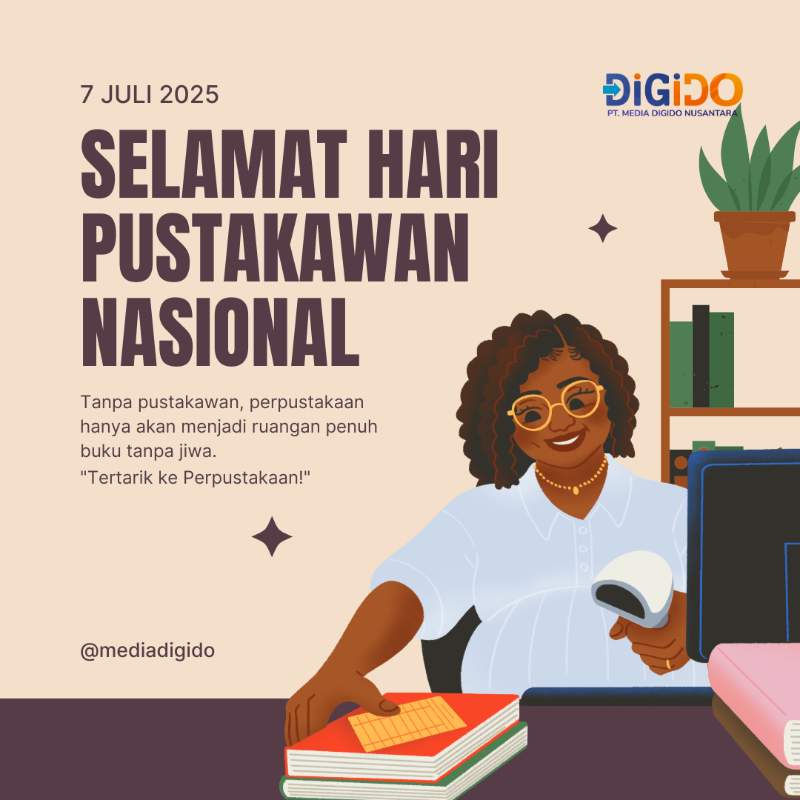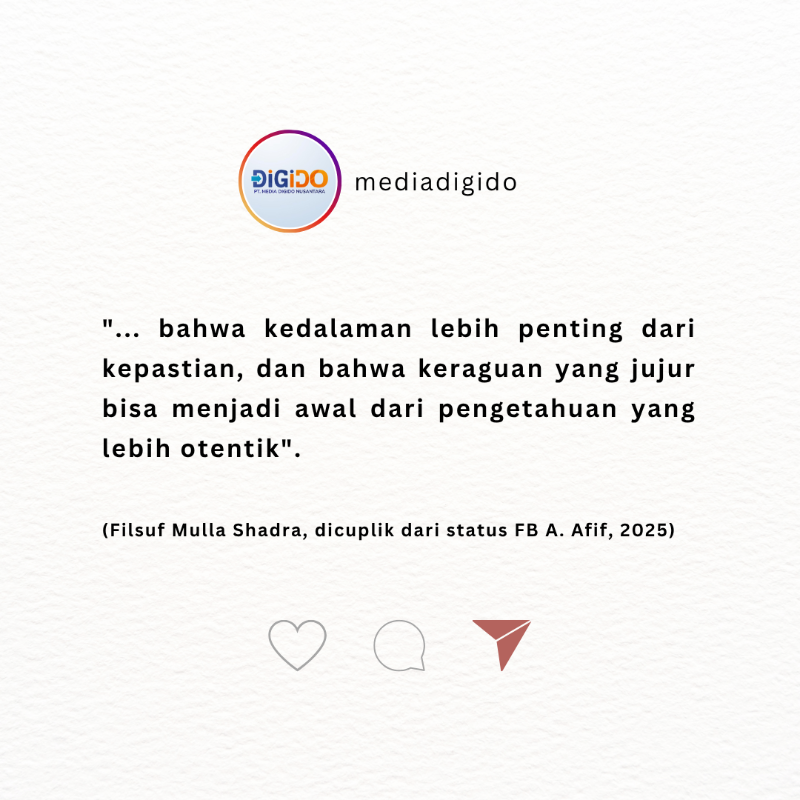Di sini, di Jogja,
ilmu pengetahuan
tak menjadi berhala
di ruang-ruang pembelajaran
Yogyakarta, Arif Abdulrakhim - Tulisan ini disarikan dari Pengantar buku kumpulan tulisan yang berjudul ‘MENGAPA KULIAH di JOGJA?’ - Menelusur ‘way of learning’ Dunia Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Tema ini sangat relevan diangkat, karena Jogja sampai saat ini masih menjadi salah satu daerah tujuan favorit untuk mengenyam pendidikan.
Kita beruntung sekali, buku kumpulan tulisan ini mendapat dukungan dari penulis 3 perguruan tinggi besar di Yogyakarta. Dan tidak tanggung-tanggung, Bapak dan Ibu dari jajaran pimpinan perguruan tinggi sendiri yang berkenan mengabulkan permohonan kami untuk menyumbangkan tulisannya. Beliau-beliau adalah Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, dari Universitas Islam Indonesia (UII) dan sekaligus Ketua Umum APTISI. Penulis kedua, adalah Prof. Dr. Bambang Cipto, MA – dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dan penulis ketiga adalah Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti Kusumayuda, M.Sc. – dari Pembangunan Nasional Yogyakarta (UPN).
Tulisan dari beliau bertiga mampu menjawab tema buku ini, ‘Mengapa Kuliah di Jogja?’. Sekaligus mempertegas mengapa Jogja dari dulu sampai saat ini dan juga masa mendatang layak menjadi tujuan kuliah. Semuanya tidak terlepas dari nilai plus yang dimiliki Jogja, yang tak selalu dimiliki kota atau daerah lain. Mulai aspek historis, kultural, sosiologis, sampai aspek geografis dengan dimilikinya sarana penunjang berupa ‘literatur alam’. Kuliah di Jogja, pada akhirnya tidak hanya belajar di ruang formal kampus, tetapi juga di luar kampus karena telah tercipta ruang-ruang belajar yang saling menunjang.
Setiap mahasiswa yang kuliah di Jogja, tidak hanya berkesempatan mendapatkan pengalaman akademis yang berkualitas. Namun juga pengalaman spiritual atau batin yang berharga dan unik, hasil bersentuhan dengan lingkungan. Perpaduan dua hal inilah yang akan semakin melengkapi masing-masing mahasiswa saat nanti menjadi output dunia pendidikan dan hadir di masyarakat.
Para alumni PT akan menjadi manusia yang lengkap. Selain memiliki kualitas intelektual yang baik juga akan memiliki ketajaman rasa. Sehingga kehadirannya lebih bermanfaat (migunani) bagi masyarakat. Seperti filosofi yang melandasi pengembangan Budaya Pemerintahan DIY, rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa, bahwa kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa.
Bapak Edy Suandi, dari UII sekaligus Ketua Umum Aptisi, menyajikan data yang menarik terkait kualitas perguruan tinggi (PT) di Jogja. Menurut beliau (data pertahun 2014), jumlah PT di DIY kurang lebih ada 120 PT dengan rincian 116 PTS dan 4 PTN. Kemudian 8 PTS di DIY, masuk dalam 44 PTS besar di seluruh Indonesia. Bahkan apabila dirinci secara khusus, dari 12 Kopertis yang ada di Indonesia dengan jumlah PTS sekitar 3.100, DIY menjadi satu-satunya provinsi yang sudah bisa mewakili 7-8 PTS di 44 besar PTS di Indonesia.
Lalu yang menjadi pertanyaan menarik, mengapa Jogja sampai bisa memiliki rasio yang tinggi seperti di atas? Bagaimana awal mulanya? Dan sampai saat ini mengapa masih bertahan dan berkembang dunia pendidikannya?
Ketiga penulis secara konseptif memberikan penjelasan yang sama atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Bahwa aspek historis, visi Sultan Hamengku Buwono IX, dan sarana penunjang ‘literatur alam dan sosial’ begitu dominan pengaruhnya.
Bapak Bambang Cipto, dari UMY, beliau menambahkan, bahwa Jogja adalah Kota Kaum Pergerakan, Kota Kaum Pembelajar, dan Miniatur Indonesia. Beliau menuliskan, ‘Sejarah mencatat, pada masa Revolusi, Jogjakarta merupakan “taklukan terakhir” yang ingin dikuasai penjajah Belanda pada waktu itu. Dalam kata-kata Soekarno, Republik tinggal menyisakan “selebar daun payung” untuk dikuasai Belanda sehingga mendorong dilancarkannya agresi militer I (21 Juli 1947) dan agresi militer kedua (19 Desember 1948).
Semangat perjuangan, pergerakan, dan kepeloporan dari sejarah pergolakan tersebut, mampu mewariskan way of learning tersendiri bagi segala aspek kehidupan di Jogja. Terutama dunia pendidikannya. Semangat-semangat tersebut yang melandasi mengapa mahasiswa saat menginjakkan kakinya untuk kuliah di Jogja, seakan-akan ada ‘kekuatan spiritual’ yang selalu menggoda untuk berpikir eksperimental, kreatif, dan kritis. Jika saya boleh mengalegorikan, kaum pendidikan di Jogja, seakan tak rela jika ilmu pengetahuan hanya menjadi ‘berhala’ di ruang-ruang pembelajaran.
Ibu Sari Bahagiarti, lebih lanjut memaparkan tentang ‘literatur alam’. Khususnya dari aspek fisiografis dan geologis. Semua literatur alam bertebaran di Jogja dan sekitarnya. Membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Dari Gunung Merapi sampai Laut Selatan. Dari Rawa Bayat sampai Bukit Menoreh. Selalu setia menunggu mahasiswa-mahasiswa yang terusik dan tertantang untuk mengeksplorasi literatur a;am tersebut.
Bagi saya pribadi setelah membaca tulisan beliau bertiga, jika meminjam ide Bapak Edy Suandi, kuliah di Jogja adalah sebuah episode kehidupan intelektual mahasiswa dimulai. Maka saya pun tidak ragu menambahkan, bahwa episode tersebut merupakan episode dimulainya tahap ‘pencarian’. Bahkan, dengan uniknya karakter literatur alam dan sosial yang dimiliki Jogja, memungkinkan lahirnya spirit ‘pencarian’ yang berbeda dibandingkan tempat lain.
Apabila kita perhatikan sedikit mendalam atas gerak-gerik para mahasiswa di Jogja saat beraktivitas, baik di kampus maupun di luar kampus, spirit ‘pencarian’ tersebut akan terlihat atau terasa. Seakan-akan mereka terus menerus, tiada henti, dan tiada puas untuk selalu mencari dan mencari. Sebuah ‘pencarian’ yang tak berujung pada ‘menemukan’ yang dicari. Tetapi lebih penting lagi pada ‘kecanduan’ berselancar di gelombang proses pencariannya. Spirit ini sungguh bagus. Karena saat mahasiswa telah purna secara akademik dan kembali secara nyata ke masyarakat, spirit ‘pencarian’ tersebut tak akan padam dan akan terus mencari tiada henti.
Saya teringat akan falsafah hamemayu hayuning bawono, mengadung pesan spiritual agar ‘selalu’ memelihara atau menjaga keseimbangan dan kelestarian ‘alam’. Kata ‘selalu’ di kalimat itu mempunyai substansi berkelanjutan (sustainable). Dan alam sendiri mempunyai kodrat selalu terancam keseimbangannya. Dengan demikian, bukankah falsafah itu adalah sebuah falsafah hidup dengan pencarian tiada henti?
Kata Zabalawi (ST Sunardi), bukankah, siapa yang terus menerus mencari, tidaklah akan menemukan, tetapi akan ditemukan?
Selamat membaca dan mencari.
*Tulisan ini pernah dimuat sebagai Pengantar Buku Untuk Indonesia, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Diedit seperlunya.
Digido News
Info dan kerja sama Email: admin@digido.co.id - WA: 081128285685